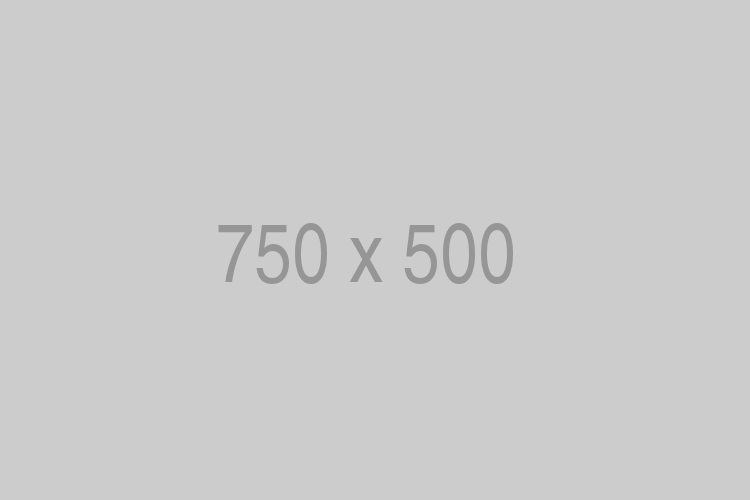Menimbang Asas Keadilan dan Kemanfaatan dalam Menyikapi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

IMPLIKASI dari putusan ini bukan hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyentuh aspek konstitusional dan demokratis yang sangat mendalam
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 telah menimbulkan polemik yang sangat luas. Putusan ini memisahkan Pemilu Legislatif tingkat daerah (DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Pemilu Nasional, serta menetapkan bahwa pelaksanaannya dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun setelah Pemilu Nasional tahun 2029.
Sedangkan Pemilu Nasional sendiri nantinya hanya akan memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK tersebut berpotensi melanggar ketentuan konstitusional mengenai siklus pemilu lima tahunan, khususnya bagi DPRD yang merupakan bagian dari Pemilu Nasional. Implikasi dari putusan ini bukan hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyentuh aspek konstitusional dan demokratis yang sangat mendalam.
Dalam kondisi apa pun, sekalipun disertai alasan yang kuat dan argumentasi akademis yang dilengkapi dengan rancangan masa transisi, putusan ini tetap dapat diperdebatkan dengan alasan tandingan yang sama-sama kuat, logis, dan rasional. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
Belakangan ini muncul pendapat lain bahwa putusan MK—khususnya yang terkait penundaan pemilu DPRD—tidak melanggar konstitusi. Pendapat tersebut bahkan menawarkan solusi berupa pemilu DPRD sementara, atau pemilu sela, untuk jangka waktu 2,5 tahun. Padahal, dalam konstitusi tidak terdapat norma mengenai pemilu sementara atau pemilu sela, apalagi yang hanya berlaku untuk DPRD dalam masa jabatan 2,5 tahun. Konstitusi secara tegas mengatur bahwa pemilu DPRD diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
Dengan demikian, apa pun istilah dan mekanisme yang digunakan, penyelenggaraan pemilu DPRD yang tidak berlangsung setiap lima tahun tetap berpotensi melanggar konstitusi.
Situasi ini ibarat buah simalakama. Di satu sisi, menjalankan putusan tersebut berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Namun di sisi lain, jika putusan tersebut tidak dijalankan, Pemerintah dan DPR dapat dianggap mengabaikan kewajiban konstitusional untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (final and binding).
Penegasan mengenai sifat final dan mengikat ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Sebelumnya, saya telah menulis beberapa artikel, antara lain “MK Bak ‘Anak Macan’ yang Menggigit Induknya Sendiri,” “Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Solusi Reformasi atau Masalah Baru?”, dan “Mungkinkah Rakyat Akan Melawan Putusan MK?” Dalam artikel-artikel tersebut, pada intinya saya menekankan bahwa putusan ini justru lebih banyak menimbulkan persoalan baru ketimbang menyelesaikan persoalan lama.
Sebagai bagian dari sikap kritis saya, saya juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan pokok perihal: “Dugaan Pelanggaran Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Permohonan Sidang Etik Kepada Hakim MK serta Info Soal Kemungkinan Melakukan JR atas Putusan MK.” Ini saya anggap sebagai langkah moral dan konstitusional untuk menjaga integritas hukum dan sistem ketatanegaraan.
Putusan ini memunculkan sejumlah persoalan serius. Di antaranya:
Pertama, putusan MK berpotensi melewati batas kewenangan yudikatif dalam sistem trias politica. Desain dan jadwal pemilu adalah bagian dari open legal policy yang menjadi domain legislator, yakni DPR dan pemerintah. Dengan kata lain, keputusan ini dapat dipandang sebagai intervensi lembaga yudikatif terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif.
Kedua, putusan MK menciptakan ketidakjelasan status konstitusional DPRD. Pasal 22E UUD 1945 secara eksplisit menyebut bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, DPRD adalah bagian dari Pemilu Nasional. Jika pemilu DPRD dipisahkan, maka secara konstitusional posisi ini menjadi ambigu dan berpotensi melanggar UUD 1945.
Ketiga, status Pilkada menjadi semakin kabur. Sejak 2009, Pilkada telah dimasukkan ke dalam rezim pemilu, dan sengketanya diselesaikan oleh MK. Jika kini Pilkada dianggap bukan bagian dari pemilu nasional, maka konsekuensinya bisa mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Agung, sebagaimana sebelum 2009. Ini justru mengembalikan sistem ke titik awal yang sebelumnya telah diperbaiki.
Keempat, terdapat kecurigaan atas adanya motif politik di balik putusan MK ini. Meski disampaikan dengan narasi akademik dan normatif tentang perbaikan demokrasi, tidak sedikit pihak yang menduga bahwa pemisahan pemilu ini menguntungkan kelompok politik tertentu. Apalagi jika hal tersebut membuka jalan bagi perpanjangan jabatan kepala daerah atau DPRD tanpa proses elektoral.
Kelima, konsekuensi praktis dari pemisahan ini sangat berat: dua kali tahapan, dua kali anggaran, dua kali kerja aparat keamanan, logistik, dan potensi konflik sosial yang lebih tinggi. Negara akan dibebani dengan risiko administratif dan politik yang tidak kecil.
Keenam, keterpaksaan publik menerima keberadaan Pejabat (Pj) Kepala Daerah demi menunggu penyelenggaraan Pilkada adalah bentuk luka demokrasi yang mendalam. Ini mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan membuka ruang bagi pengisian jabatan publik tanpa mandat elektoral. Jika hal ini terus berlangsung, maka perampasan kedaulatan rakyat akan menjadi hal yang dilegalkan melalui norma hukum formal.
Sesungguhnya, masih banyak alasan lain yang logis dan masuk akal untuk mengimbangi argumen dari pihak penggugat maupun Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri. Salah satu contohnya adalah potensi hilangnya hak demokratis rakyat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2029, baik sebagai calon anggota DPRD maupun kepala daerah. Ya, selain itu, masih banyak lagi alasan lain yang juga rasional dan patut dipertimbangkan.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan ini, saya melihat bahwa hal tersebut berpotensi menimbulkan pro dan kontra yang tak berkesudahan. Situasi ini dapat berkembang menjadi kerumitan dalam aturan ketatanegaraan yang berujung pada kebuntuan (deadlock). Bahkan, dalam kondisi tertentu, tidak tertutup kemungkinan akan memicu kegaduhan besar di tengah masyarakat.
Untuk mencari solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh Putusan MK tersebut, saya berpendapat dan mengusulkan agar Pemerintah dan DPR mempertimbangkan kemungkinan untuk mengesampingkan putusan tersebut dengan berlandaskan pada asas keadilan dan kemanfaatan. Kedua asas ini merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum. Asas keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan layak bagi seluruh warga negara, sementara asas kemanfaatan menyoroti sejauh mana hukum memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan politik bangsa.
Penerapan kedua asas tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam doktrin hukum progresif, serta sesuai dengan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jika sebuah putusan hukum menimbulkan keresahan, ketidakpastian hukum, hingga membahayakan stabilitas demokrasi, maka demi keadilan substantif, negara dapat dan perlu mengambil sikap yang bijaksana.
Konstitusi bukanlah teks kaku yang membelenggu nalar publik dan kehendak demokratis rakyat. Justru sebaliknya, konstitusi adalah alat untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak dirampas oleh tafsir-tafsir yang manipulatif. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Oleh karena itu, jika Putusan MK membuka ruang bagi jabatan publik yang tidak melalui pemilihan langsung, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Ini adalah bentuk konstitusionalisasi kekuasaan tanpa legitimasi rakyat. Lebih jauh, jika MK sendiri menafsirkan konstitusi secara lentur demi mendukung kebijakan tertentu, maka rakyat patut bertanya: siapa yang menjaga konstitusi, jika Mahkamah Konstitusi justru menjadi bagian dari masalah?
Dalam kondisi ini, penting bagi DPR dan Pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendorong revisi terbatas atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, atau bahkan amandemen terbatas terhadap UUD 1945 jika diperlukan. Tentu dengan prinsip kehati-hatian, keterlibatan publik, dan transparansi penuh.
Apa pun langkah yang diambil, keputusan harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas demokratis dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Tidak boleh ada keputusan yang lahir dari tafsir hukum sempit yang justru menimbulkan luka konstitusi dan krisis kepercayaan publik.
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, betapapun dimaksudkan sebagai solusi reformasi, justru berisiko menjadi masalah besar yang rumit, sulit, ruwet, dan bikin mumet. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapinya. Bukan hanya oleh DPR dan Pemerintah, tapi juga oleh seluruh elemen masyarakat sipil yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia.