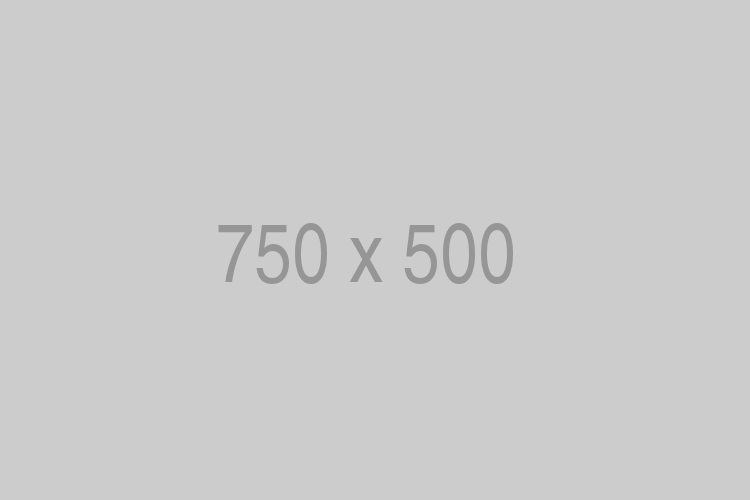Mungkinkah Rakyat Akan Melawan Putusan MK? Atau Memulainya dengan Melaporkan ke MKMK

PUTUSAN MK itu menimbulkan polemik luas, yang kemudian berbuntut pada pelaporan Ketua MK saat itu, Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena dugaan pelanggaran kode etik.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Tak satu pun lembaga atau institusi di negeri ini yang memiliki kewenangan untuk membatalkan atau melonak putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Asas final and binding, atau yang dikenal dengan istilah “final dan mengikat”, adalah senjata hukum yang paling kuat yang dimiliki MK.
Keputusan MK tidak bisa diganggu gugat dan wajib dilaksanakan oleh siapa pun, tanpa kecuali. Inilah sumber kekuatan MK yang menjadikannya sebagai pilar penentu dalam sistem ketatanegaraan kita. Maka dalam konteks hukum positif, siapa pun yang mencoba menentang keputusan MK akan diposisikan sebagai pihak yang melanggar konstitusi.
Karena itu, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 dibacakan pada 26 Juni 2025, saya menahan diri untuk tidak langsung bersuara. Bukan karena saya tidak memahami implikasi putusan tersebut, tetapi karena saya menyadari betul bahwa setiap kritik terhadap keputusan MK akan dihadapkan pada tembok kokoh bernama final dan mengikat.
Selain itu, saya juga yakin para hakim MK telah mempertimbangkan potensi serangan publik terkait kemungkinan pelanggaran konstitusional yang timbul dari putusan tersebut. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa mereka telah menyiapkan argumentasi hukum yang kuat beserta mekanisme perlindungan terhadap keputusannya.
Untuk memahami konteks ini, mari kita mengingat kembali salah satu kasus penting yang pernah diputus MK. Pada 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Putusan MK itu menimbulkan polemik luas, yang kemudian berbuntut pada pelaporan Ketua MK saat itu, Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) karena dugaan pelanggaran kode etik. Dalam putusannya, MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi. Kemudian, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Namun, meskipun terjadi pelanggaran etik berat, Putusan MK dalam perkara tersebut tetap berlaku dan tidak dibatalkan. Hal ini membuktikan bahwa sifat final and binding dari putusan MK benar-benar tidak dapat diganggu gugat, meskipun terdapat pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan.
Situasi serupa juga terjadi dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh seluruh elemen negara, termasuk pemerintah, DPR, KPU, dan rakyat. Menolak atau mengabaikannya berarti melanggar konstitusi. Namun, terdapat persoalan mendasar yang membuat situasinya berbeda. Pelaksanaan putusan MK ini justru menimbulkan polemik baru yang sangat krusial, karena berpotensi melanggar konstitusi itu sendiri.
Putusan tersebut mengubah sistem ketatanegaraan secara mendasar dengan memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD kini harus diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal yang memilih DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota, dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun.
Secara sepintas, putusan ini tampak sebagai langkah reformasi. Namun secara substansial, terdapat sejumlah persoalan konstitusional yang cukup serius.
Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD. Tidak ada penyebutan tentang pemilu nasional dan pemilu lokal sebagai dua entitas berbeda. Maka, memisahkan pemilu DPRD dari pemilu nasional berpotensi menciptakan kategori pemilu yang tidak dikenal dalam konstitusi.
Pemilu DPRD secara konstitusional merupakan bagian dari pemilu nasional. Jika jadwalnya dipisahkan, sangat mungkin masa jabatan anggota DPRD akan diperpanjang untuk menyesuaikan dengan waktu pemilu yang baru. Hal ini bertentangan dengan prinsip periodisasi lima tahunan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pemisahan jadwal pemilu juga dikhawatirkan akan memperpanjang masa jabatan kepala daerah tanpa melalui proses elektoral. Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya pergantian kepala daerah melalui mekanisme penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah.
Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa putusan MK tersebut berpotensi merugikan hak-hak demokratis rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, putusan MK itu membuka ruang bagi konstitusionalisasi jabatan publik tanpa mandat rakyat, yang jelas merupakan bentuk perampasan terhadap kedaulatan rakyat.
Khusus terkait jabatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah, berikut catatan penting yang ingin saya sampaikan:
“Keterpaksaan publik untuk menerima keberadaan Pejabat (Pj) Kepala Daerah demi terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 merupakan bentuk pengorbanan besar dalam demokrasi. Jelas, ini adalah luka demokrasi yang semestinya tidak perlu terulang. Bagaimana mungkin, ketika rakyat seharusnya menggunakan hak demokrasinya untuk memilih kepala daerah secara langsung, justru hak tersebut dirampas oleh aturan yang tidak demokratis melalui mekanisme penunjukan Pj? Ini adalah preseden yang tidak boleh dibiarkan terjadi kembali.”
Selain itu, putusan MK tersebut juga menunjukkan kecenderungan penafsiran konstitusi yang terlalu lentur. Jika Mahkamah Konstitusi—sebagai guardian of the constitution—justru menafsirkan konstitusi secara sepihak demi mendukung kebijakan tertentu, maka kredibilitas dan netralitas lembaga ini patut dipertanyakan.
Jika MK sendiri melanggar konstitusi, siapa yang memiliki kewenangan untuk membatalkannya? Siapa sebenarnya yang menjaga konstitusi? Apakah jawabannya tetap rakyat?
Dalam konteks tersebut, bila masyarakat benar-benar menyadari bahwa keputusan tersebut secara substantif merampas hak kedaulatan mereka, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang protes. Kemarahan publik bisa meluas dan menuntut pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan, bahkan mungkin bisa sampai pada tuntutan pembubaran MK atau reformasi kelembagaan secara menyeluruh.
Dalam konteks ini perlu kita perhatikan ketentuan dasar soal Kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini bukan sekadar slogan, melainkan landasan konstitusional bahwa rakyat adalah pemilik otoritas tertinggi dalam kehidupan bernegara.
Artinya, rakyatlah yang berhak menentukan arah kebijakan politik dan pemerintahan, termasuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya secara berkala.
Andaikan semua orang benar-benar memahami hak demokratis mereka, tentu hal itu akan menjadi peringatan bagi siapa pun untuk bertindak lebih hati-hati. Namun demikian, langkah rakyat tidak bisa serta-merta diwujudkan dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap putusan MK. Sebagai langkah awal, masyarakat sebaiknya menempuh jalur etik dengan melaporkan para hakim MK yang terlibat dalam pengambilan putusan tersebut kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Laporan dari rakyat atas keputusan MK tersebut menjadi sangat penting. Tujuannya yakni, untuk menguji netralitas dan integritas para hakim serta menilai apakah terdapat pelanggaran etika dalam proses pengambilan putusan. Langkah ini sah dan legal dalam kerangka negara hukum.
Tentu, perlu diakui bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari niat baik dalam memperbaiki sistem demokrasi dan hukum di Indonesia. Namun, perbaikan semestinya dilakukan secara bertahap, partisipatif, dan tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru. Keputusan yang terburu-buru, apalagi berisiko menabrak konstitusi, justru menjadi masalah yang lebih besar dari solusi yang hendak ditawarkan.
Karena itu, semua pihak—masyarakat sipil, akademisi, partai politik, dan lembaga negara—perlu mendorong dialog terbuka serta melakukan evaluasi serius terhadap putusan MK tersebut.
Dalam konteks ini lembaga DPR lah yang sangat memiliki ruang untuk merespons, baik melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun melalui amandemen terbatas terhadap UUD 1945, jika memang diperlukan. Sebab, jika dibiarkan, sangat mungkin masa depan demokrasi Indonesia akan dikendalikan oleh tafsir hukum yang menyimpang, bukan oleh suara rakyat yang berdaulat.