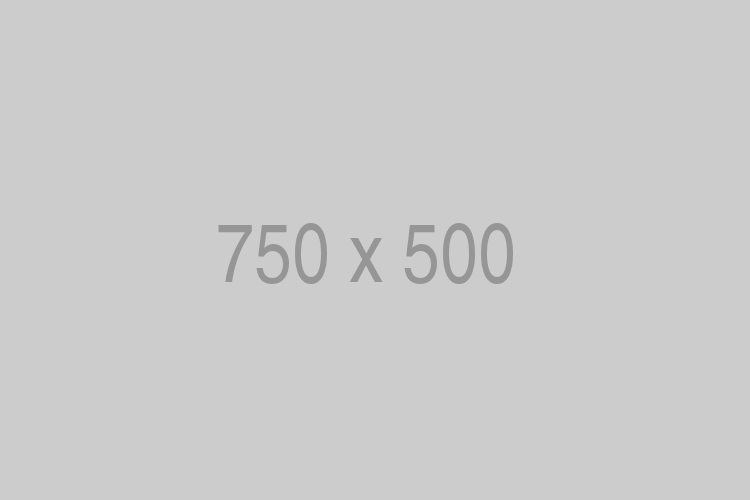Lima Menteri Layak Bertanggung Jawab atas Banjir dan Longsor di Sumatera

MUSIBAH ini tidak dapat dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Saya terpanggil menulis artikel ini menyusul musibah banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ini merupakan kali kempat saya mengangkat topik tentang banjir dan longsor tersebut, setelah sebelumnya menerbitkan tiga artikel yang seluruhnya merupakan ungkapan duka dan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di Pulau Sumatra.
Ketiga artikel sebelumnya masing-masing berjudul: “Surat Terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tentang Usulan Pembentukan Tim Khusus Bantuan untuk Korban Banjir–Longsor di Sumatra,” “Gerakan Gotong Royong Kolosal Nasional untuk Bencana di Sumatra Lebih Penting daripada Perdebatan Status Bencana Nasional,” dan “Duka Banjir di Sumatra yang Bercampur Amarah: Negara Harus Hadir untuk Menegakkan Hukum.”
Motivasi saya tetap sama: keprihatinan sebagai bagian dari anak bangsa dan kecintaan terhadap lingkungan—hutan, sungai, dan keseimbangan alam. Saya percaya setiap warga yang mencintai NKRI pasti merasakan duka dan solidaritas atas musibah yang terjadi di Sumatra. Hanya mereka yang kehilangan nurani yang dapat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap penderitaan para korban.
Dalam semua artikel tersebut saya menekankan bahwa prioritas utama—baik bagi pemerintah maupun masyarakat—adalah bantuan kemanusiaan segera dan pemulihan fisik (rumah, fasilitas umum, infrastruktur). Debat yang tidak perlu harus dikerdilkan; seharusnya upaya mengembalikan normalitas dan keselamatan rakyat menjadi fokus utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, melihat skala kerusakan dan korban yang telah sangat besar, pendekatan itu saja tidak cukup. Kita juga harus mencari akar penyebab banjir dan longsor — dan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang relevan: pengusaha, masyarakat, maupun aktor lain yang terlibat dalam perusakan lingkungan di Sumatra.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan update pada 4 Desember 2025: korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 836 orang. Angka ini menunjukkan bahwa bencana ini bukan insiden kecil — melainkan bencana besar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
Dalam konteks tersebut, saya menyoroti kinerja kementerian terkait yang, menurut saya, layak dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas terjadinya banjir dan longsor yang merugikan masyarakat luas. Jabatan menteri adalah posisi publik yang sewajarnya dievaluasi dan dikritisi ketika terjadi musibah besar yang menyita perhatian seluruh rakyat di negeri ini.
Kelima menteri yang, menurut saya, layak dimintai pertanggungjawaban adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Fasil Nurofia; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid; serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo. Musibah ini tidak dapat dipandang sebagai bencana alam semata, melainkan sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang.
Dalam konteks musibah banjir dan longsor di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—saya telah mempelajari dan menganalisis berbagai kajian serta penjelasan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Selain itu, penjelasan dari Greenpeace juga menjadi rujukan penting yang saya pelajari, termasuk uraian rinci para pakar, di antaranya Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab banjir dan longsor di Sumatra—baik dari WALHI, Greenpeace, telah disampaikan secara jelas dan gamblang. Karena itu, kesimpulannya adalah bahwa banjir besar yang melanda Pulau Sumatra pada akhir November hingga awal Desember 2025 bukan semata-mata bencana alam akibat hujan ekstrem, melainkan juga cerminan kegagalan manajemen lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang melibatkan unsur pemerintahan.
Lebih jauh, penjelasan Pakar UGM Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., yang juga Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS, menegaskan bahwa banjir dan longsor yang terjadi bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola meningkatnya bencana hidrometeorologi dalam dua dekade terakhir. Kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) telah mengikis daya serap alam dan mempercepat luapan air hujan sehingga memperbesar risiko banjir dan longsor.
Dalam pandangan Hatma, kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS telah menghilangkan daya dukung dan daya tampung kawasan untuk meredam curah hujan tinggi. Hilangnya tutupan hutan berarti hilangnya fungsi-fungsi penting hutan dalam mengendalikan daur air melalui proses intersepsi, infiltrasi, evapotranspirasi, serta pengurangan erosi dan limpasan permukaan.
Masih merujuk pada penjelasan pakar UGM tersebut, kerusakan hutan di hulu menjadi pemicu awal terjadinya erosi masif dan longsor yang kemudian bermuara pada banjir bandang. Hutan di wilayah hulu berperan sebagai penyangga hidrologis; vegetasi yang rimbun bekerja layaknya spons raksasa yang menyerap air hujan dan menahannya agar tidak langsung mengalir ke sungai.
Tidak dapat dibantah bahwa bencana kali ini terjadi dalam skala yang sangat besar. Tingginya angka kematian, pengungsian massal, dan kerugian materiil menjadi bukti kuat betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan. Ratusan orang meninggal, ribuan rumah rusak, puluhan ribu warga mengungsi, kerugian mencapai triliunan rupiah, dan jutaan masyarakat terdampak secara langsung.
Dalam kondisi seperti ini, wajar jika publik menuntut pertanggungjawaban dari para menteri yang mendapat mandat menjaga lingkungan dan merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak menuntut akuntabilitas dari para pembantu Presiden, apalagi Presiden sebagai pemberi mandat juga dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.
Kegagalan kebijakan dan pengawasan ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab langsung dari pejabat pemerintahan yang memegang wewenang atas sektor lingkungan dan sumber daya alam — termasuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan, dan Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ketiganya menjadi sorotan karena dinilai gagal mencegah kerusakan lingkungan di hulu yang kemudian berkembang menjadi krisis ekologis.
Tidak hanya tiga menteri tersebut, dua menteri lainnya — yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo — juga layak menjadi perhatian. Hal ini karena terdapat keterkaitan tugas, kewenangan, serta hasil kinerja dan kebijakan mereka yang secara logis dan relevan berkaitan dengan besarnya dampak banjir dan longsor di Sumatra.
Presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk mengevaluasi secara serius kinerja para menteri tersebut. Apabila terbukti bahwa kebijakan perizinan, pengawasan lingkungan, atau tata ruang diterapkan secara lemah, pengendalian dan normalisasi sungai terlambat, atau bahkan diabaikan, tindakan tegas termasuk pencopotan jabatan bukan saja wajar tetapi diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Kerusakan di hulu DAS menjadi faktor kunci yang selama ini tampaknya diabaikan. Penurunan tutupan hutan yang dipicu oleh deforestasi, alih fungsi lahan, perkebunan, dan pertambangan telah mengurangi kapasitas tanah dalam menyerap air. Dampaknya adalah peningkatan limpasan permukaan dan kerentanan longsor ketika hujan ekstrem datang.
Jejak izin pertambangan dan aktivitas minerba memperparah keadaan. Sejumlah data informasi dan pemberitaan media daring menunjukkan bahwa banyak izin tambang berada dekat dengan sungai dan lereng curam, ditambah dengan praktik pembalakan dan reklamasi yang tidak memadai. Dalam sejumlah lokasi, kayu-kayu besar hanyut bersama air bah, menjadi bukti bahwa kerusakan hutan di hulu berkontribusi langsung terhadap banjir bandang dan longsor.
Kerusakan hutan di wilayah hulu telah menghilangkan fungsi ekologis yang sangat penting, seperti penahan tanah dan pengatur aliran air melalui jaringan akar pohon. Ketika hujan ekstrem turun, tanah kehilangan stabilitasnya sehingga longsor di tebing, banjir kayu (log flood), penyempitan alur sungai akibat sedimen, dan luapan air besar sangat mudah terjadi.
Selain itu, persoalan tata ruang juga berpotensi memperburuk situasi. Kelemahan dalam pengendalian alih fungsi lahan, ketiadaan penetapan zona rawan bencana yang jelas, serta rendahnya implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memungkinkan aktivitas pemukiman, perkebunan, industri, dan pertambangan masuk ke wilayah yang sebenarnya harus dilindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Kementerian ATR/BPN sangat penting dan patut dievaluasi.
Aspek infrastruktur yang berada di bawah Kementerian PUPR juga tampak berkontribusi terhadap besarnya dampak bencana. Boleh jadi banyak sungai mengalami penyempitan, sedimen dari hulu tidak tertahan, dan normalisasi tidak dilakukan secara memadai. Boleh jadi sistem drainase perkotaan di sejumlah kota seperti Medan dan Padang sudah sejak lama tidak mampu menampung debit air tinggi. Akibatnya, ketika banjir besar datang dari hulu, wilayah hilir langsung terendam tanpa adanya mekanisme mitigasi yang efektif.
Keseluruhan permasalahan—mencakup izin pertambangan, kehutanan, tata ruang, lingkungan, dan infrastruktur—sejatinya harus saling terintegrasi. Namun mungkin saja terjadi bahwa koordinasi antarkementerian lemah dan pengawasan minim. Bencana di Sumatra ini boleh jadi merupakan titik temu dari kegagalan kebijakan di lima kementerian yang saling berkaitan dan memiliki kewenangan langsung terhadap isu-isu kritis tersebut.
Melihat skala korban, kerusakan lingkungan, dan dampaknya terhadap jutaan warga, jelas bahwa negara tidak hanya membutuhkan upaya penanganan darurat dan rehabilitasi. Dalam kondisi ini, ada dua hal yang wajib dijalankan sekaligus: selain memberikan bantuan cepat bagi para korban, negara juga harus menuntut pertanggungjawaban yang konkret dan sistematis dari institusi yang memiliki mandat melindungi lingkungan dan keselamatan rakyat.
Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan pascabencana, tetapi juga sebagai pelindung hak dasar rakyat untuk hidup aman, mendapatkan lingkungan yang sehat, dan menikmati tata ruang yang tertata dengan baik. Tanpa kejelasan pertanggungjawaban dan perbaikan tata kelola, tragedi serupa akan mudah terulang. Pemerintah memiliki dasar konstitusional dan mandat moral untuk melakukan audit menyeluruh atas seluruh izin tambang di hulu DAS, mengambil tindakan tegas terhadap kementerian atau lembaga yang lalai, termasuk mencopot menteri apabila terbukti gagal menjalankan amanat konstitusi.
Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan kritis, memperkuat sistem pengawasan lingkungan dan tata ruang, menata ulang kebijakan zonasi dan manajemen lingkungan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai, bendungan, dan sistem drainase. Mitigasi kawasan rawan bencana juga harus menjadi program wajib yang dijalankan secara terencana dan transparan.
Sejalan dengan dorongan berbagai elemen masyarakat sipil dan tokoh politik yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan, termasuk perizinan tambang dan alih fungsi lahan, kini saatnya pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan keadilan ekologis dan melindungi kehidupan masyarakat. Bencana Sumatra 2025 menjadi alarm keras bahwa alam tidak dapat terus dieksploitasi tanpa tanggung jawab. Negara harus hadir bukan hanya di saat duka, tetapi juga di saat pencegahan dan penjagaan keselamatan rakyat.