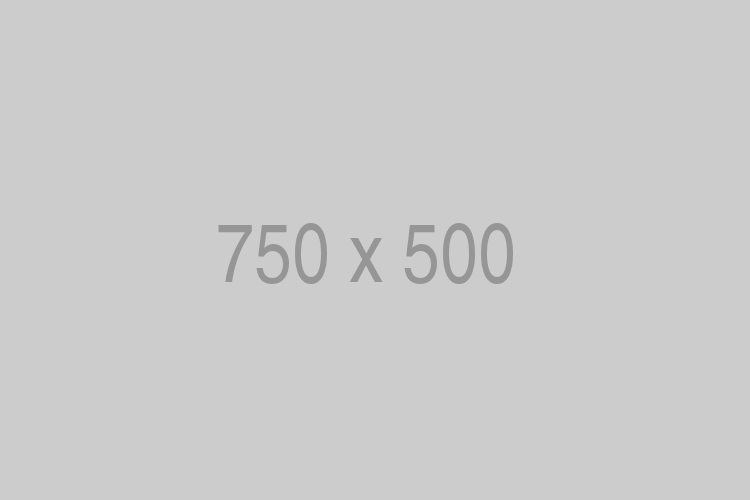Konten Pejabat Publik Gratifikasi? KPK Harus Tegas

NEGARA telah memberikan gaji dan fasilitas resmi yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, pejabat publik tidak sepantasnya mencari penghasilan tambahan lain, apalagi dengan cara yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Monetisasi konten digital—baik berupa video, tulisan, podcast, maupun gambar—memang menggiurkan karena mampu menghasilkan pendapatan besar. Godaan ini ternyata juga menyentuh sebagian pejabat publik yang melihat peluang menambah penghasilan dengan memanfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya.
Padahal, integritas semestinya menjadi fondasi utama seorang pejabat publik. Integritas adalah dasar kepercayaan rakyat terhadap negara. Begitu seseorang diberi amanah kepemimpinan—baik sebagai kepala daerah, menteri, maupun pejabat publik lainnya—ia telah menerima tugas mulia yang menuntut seluruh tenaga, pikiran, dan perhatian tercurah penuh pada kepentingan negara, bukan diarahkan untuk mengejar keuntungan pribadi.
Negara telah memberikan gaji dan fasilitas resmi yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, pejabat publik tidak sepantasnya mencari penghasilan tambahan lain, apalagi dengan cara yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat. Hal ini termasuk penghasilan dari konten media sosial, sebab jabatan publik melekat pada diri pejabat dan sering kali menjadi faktor utama yang mendatangkan keuntungan digital tersebut. Dengan kata lain, pendapatan itu lahir karena adanya jabatan, bukan semata karena kreativitas personal.
Dalam perspektif hukum, penghasilan semacam itu patut dipandang sebagai bentuk gratifikasi. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah sudah ada aturan yang secara tegas mengkategorikan pendapatan dari monetisasi konten pejabat publik sebagai gratifikasi? Di sinilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersikap tegas dan mendorong lahirnya aturan khusus yang mengatur persoalan ini.
Gratifikasi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 12B ayat (1). Dalam ketentuan tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, layanan kesehatan cuma-cuma, atau bentuk keuntungan lain yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban pejabat.
Undang-undang juga menetapkan bahwa setiap pejabat negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan. Jika kewajiban ini diabaikan, penerima dapat dikenakan sanksi berat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Sebaliknya, jika gratifikasi dilaporkan sesuai prosedur, penerima dibebaskan dari ancaman pidana.
Meski ada pengecualian, seperti hadiah dari keluarga, suvenir seminar, perangkat promosi, atau honorarium profesi yang tidak berkaitan dengan jabatan, ruang abu-abu tetap terbuka lebar. Di era media sosial, monetisasi yang tidak transparan sangat rawan disalahgunakan, dan celah ini bisa menjadi pintu masuk praktik gratifikasi terselubung.
Karena itu, peran KPK menjadi sangat penting. Lembaga antirasuah perlu memperluas koridor hukum dan mendorong lahirnya aturan baru yang secara eksplisit mengkategorikan penghasilan dari monetisasi media sosial pejabat sebagai gratifikasi. Setiap penghasilan yang timbul karena jabatan—baik melalui endorsement, sponsorship, maupun monetisasi platform digital—harus dicatat dan dilaporkan. Langkah ini akan memperkuat transparansi serta mencegah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah pun sudah sepatutnya mewajibkan pejabat publik menutup akun media sosial pribadi yang menghasilkan pendapatan, atau minimal mengubahnya menjadi akun non-komersial yang tidak bisa dimonetisasi. Akun komersial pejabat berpotensi menjadi mesin penggalangan dana pribadi dengan memanfaatkan jabatan dan jumlah pengikut yang besar. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip amanah publik, karena jabatan negara bukanlah sarana mencari keuntungan tambahan, melainkan amanat untuk melayani rakyat.
Bahaya yang lebih serius adalah lahirnya pejabat yang lebih sibuk mengejar popularitas dan keuntungan dari konten viral ketimbang bekerja sepenuh hati untuk masyarakat. Jika pendapatan dari media sosial melebihi gaji resmi, maka keberpihakan pejabat pada kepentingan rakyat akan terancam. Pada akhirnya, rakyat pembayar pajak yang telah membiayai gaji mereka justru dirugikan karena pelayanan publik terganggu oleh ambisi pribadi.
Untuk mencegah hal tersebut, KPK perlu memformalkan penghasilan media sosial pejabat sebagai bagian dari gratifikasi yang wajib dilaporkan. Definisi gratifikasi juga harus diperluas dalam peraturan internal agar mencakup praktik monetisasi digital. Selain itu, pejabat publik wajib menutup atau mengubah akun pribadinya menjadi akun resmi non-komersial yang dikelola secara transparan.
Langkah-langkah ini akan menjaga integritas pejabat publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan jabatan negara tidak dikecilkan menjadi sekadar sumber pendapatan pribadi. Seorang pemimpin sejati seharusnya berhenti mengejar keuntungan dari popularitas digital, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya demi kepentingan rakyat.