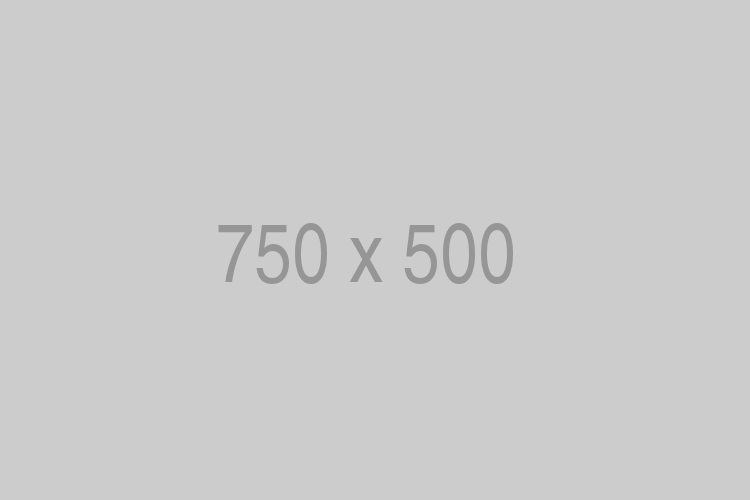Merdeka dengan Darah dan Utang Perang: Demi Negara Maju dan Rakyat Sejahtera, Perlukah Hukuman Mati bagi Para Koruptor?

HANYA dengan langkah keras dan berani, bangsa ini bisa terbebas dari cengkeraman korupsi
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, saya melanjutkan penulisan artikel ini. Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari dua artikel saya sebelumnya yang berjudul “Merdeka dengan Utang: Negara Harus Tuntut Ganti Rugi atas Utang ke Belanda Beserta Bunga Sejak 1949, Senilai USD 1,13 Miliar (4,3 Miliar Gulden),” dan “Presiden Prabowo Perlu Menuntut Ganti Rugi Utang Warisan Belanda: Sri Mulyani Harus Menghitung dengan Bunga Sejak 1949, Senilai USD 1,13 Miliar.”
Mengurai persoalan bangsa ini perlu ditinjau dengan menoleh pada sejarah panjang Nusantara. Untuk memudahkan, mari kita mulai dari masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang paling masyhur menyebutkan bahwa beliau lahir pada 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah, bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi.
Saya memilih merujuk pada kelahiran Nabi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga lebih mudah dijadikan titik awal gambaran sejarah.
Jauh sebelum itu, Nusantara telah memiliki kerajaan besar. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Setelahnya bermunculan kerajaan dan kesultanan lain yang menjadi fondasi lahirnya bangsa Indonesia hingga akhirnya menyatu dalam kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Sementara itu, di belahan dunia lain, negara-negara besar baru lahir jauh setelah Nusantara mengenal peradaban. Inggris resmi berdiri pada 927 Masehi, Spanyol dan Portugal sekitar abad ke-15, Prancis modern lahir lewat revolusi pada 1792–1804, sedangkan Kerajaan Belanda terbentuk pada 1815 setelah kekalahan Napoleon Bonaparte. Bahkan sebelum berdiri sebagai kerajaan, Belanda sempat berada di bawah kekuasaan Prancis dengan nama Republik Bataaf pada 1795.
Ironisnya, pada masa mereka sendiri masih berada di bawah dominasi Prancis, Belanda justru datang ke Nusantara. Sejak 1800 hingga 1945, Belanda bercokol di bumi Indonesia, mengeruk kekayaan alam dan memperalat para raja serta sultan lokal demi keuntungan sepihak. Ketika Jepang kalah dari Sekutu pada Perang Dunia II, Belanda kembali mencoba menancapkan kuku kolonialnya, padahal Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Namun perjuangan belum usai. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, itupun dengan syarat yang menyesakkan dada: Indonesia harus menanggung utang Belanda sebesar 1,13 miliar dollar atau 4,3 miliar gulden, yang sejatinya merupakan biaya agresi mereka sendiri di tanah air ini. Dari sinilah kita sadar bahwa kemerdekaan bangsa ini benar-benar ditebus dengan darah para pejuang sekaligus dengan beban utang perang.
Sayangnya, setelah merdeka, bangsa ini menghadapi musuh baru yang tak kalah ganas: korupsi. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terus merajalela. Negeri yang kaya raya dengan hasil bumi ini justru tak bisa memberi kesejahteraan yang layak bagi rakyatnya karena kekayaannya digerogoti oleh para pengkhianat bangsa. Utang negara menumpuk, pajak membebani rakyat kecil, sementara pejabat dan oknum tertentu berpesta pora dengan uang rakyat.
Lantas siapa yang harus dipersalahkan? Tentu para koruptor itu. Negara-negara lain berani mengambil langkah tegas. Cina, misalnya, menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor, dan hasilnya negara itu mampu melesat menjadi kekuatan ekonomi dunia. Pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak melakukan hal serupa?
Kemajuan Tiongkok berawal dari hadirnya seorang “penjagal” menakutkan bagi para koruptor karena kebijakan kerasnya dalam memberantas korupsi. Ia adalah Zhu Rongji, Perdana Menteri Tiongkok periode 1998–2003. Bersama Presiden Jiang Zemin, Zhu Rongji membentuk duet kepemimpinan yang tegas dalam perang melawan korupsi, dengan menjatuhkan serangkaian hukuman berat, termasuk hukuman mati, kepada pejabat yang terbukti melakukan korupsi.
Kini, lebih dari tiga dekade kemudian, Tiongkok telah menjelma menjadi negara maju dan makmur.
Situasi awalnya sejatinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Era reformasi, yang dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa, membawa harapan besar bagi bangsa. Namun, reformasi di Indonesia gagal membawa negeri ini menuju kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Alih-alih memberantas korupsi, praktik korupsi justru semakin merajalela.
Dalam konteks ini, utang negara terus menumpuk. Untuk menutup defisit anggaran serta membayar cicilan pokok beserta bunga pinjaman, pemerintah terpaksa meningkatkan pungutan pajak dari rakyat. Kebijakan ini berpotensi menjadi beban yang semakin memberatkan masyarakat.
Kini sudah saatnya bangsa ini berani mengambil keputusan radikal demi masa depan. Koruptor tidak cukup hanya dijatuhi hukuman penjara, karena faktanya penjara sering kali justru menjadi tempat mereka menikmati fasilitas mewah. Hukuman yang benar-benar setimpal perlu ditegakkan. Bila perlu, hukuman mati. Atau bahkan jika memungkinkan hukum gantung bagi para koruptor dilaksanakan secara terbuka, bahkan di Monas, agar menjadi tontonan sekaligus pelajaran bagi seluruh rakyat.
Menurut data yang ada, pada tahun 2025 nilai utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp7.000–8.500 triliun. Sementara itu, utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 saja mencapai sekitar Rp 750-800 triliun. Kondisi ini terus memburuk dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan langkah darurat untuk menekan beban utang dan bunga yang kian memberatkan negeri ini.
Hanya dengan langkah keras dan berani, bangsa ini bisa terbebas dari cengkeraman korupsi. Harapannya sederhana: Indonesia yang bebas dari korupsi, maju dalam pembangunan, dan rakyatnya benar-benar merasakan kesejahteraan. Kekayaan para koruptor harus dirampas menjadi milik negara, termasuk aset para konglomerat yang memperoleh harta secara ilegal. Dengan langkah ini diharapkan terkumpul dana segar yang cukup untuk membayar beban utang beserta bunganya.