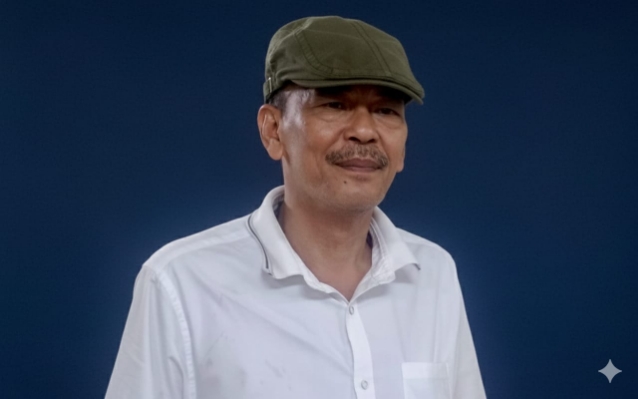Jika Ijazah Eks Presiden Jokowi dan Wapres Gibran Terbukti Bermasalah: Roy Suryo, Dr. Rismon, dr. Tifa, dan Beathor Layak Disebut Pejuang Rakyat Sejati

Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga kini belum padam. Meski pernah dinyatakan sah oleh sejumlah pejabat UGM dan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagian kalangan tetap meragukan keaslian dokumen pendidikan tersebut.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Tokoh-tokoh seperti pakar telematika Drs. KRMT Roy Suryo Notodiprojo, M.Sc., pakar forensik digital Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, ilmuwan sekaligus pegiat media sosial dr. Tifa, serta mantan anggota DPR Beathor Suryadi tetap konsisten mempertahankan sikap kritis. Mereka menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan yang, menurut pandangan mereka, layak diuji melalui mekanisme hukum maupun kajian akademik.
Atas pernyataan terbuka terkait dugaan pemalsuan ijazah tersebut, mereka harus menghadapi berbagai laporan hukum. Beberapa di antaranya dilaporkan ke pihak kepolisian. Nama Beathor Suryadi pun ikut menjadi sorotan setelah turut dilaporkan, bahkan dengan tuduhan lain, termasuk dugaan pemerasan. Seluruh persoalan ini bermula dari isu ijazah palsu, termasuk pernyataan tentang dugaan bahwa ijazah Presiden Jokowi disebut-sebut dibuat di Pasar Pramuka.
Polemik ini semakin memanas setelah KPU menyerahkan salinan ijazah yang telah dilegalisir kepada para pemohon, termasuk Roy Suryo. Langkah ini membuka ruang bagi publik untuk mengkaji ulang keotentikan dokumen yang menjadi dasar legalitas pencalonan Jokowi dalam pemilu sebelumnya.
Perdebatan pun meluas dari sekadar keaslian dokumen menjadi isu integritas negara, akuntabilitas pejabat publik, dan hak warga negara untuk memperoleh kebenaran. Dalam konteks hukum tata negara dan etika pemerintahan, keaslian ijazah bukan hanya urusan administratif, melainkan menyangkut legitimasi moral dan legal seorang pemimpin bangsa.
Kemunculan Beathor Suryadi semakin memperkuat keberanian kelompok Roy Suryo dan SC. Pernyataannya yang sangat eksplisit—menyebut dugaan bahwa ijazah Jokowi “dibuat di Pasar Pramuka”—menjadi pukulan keras yang mengguncang opini publik. Meskipun kontroversial dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, pernyataan tersebut mencerminkan tekad sebagian warga untuk tidak membiarkan keraguan publik terkubur oleh dominasi kekuasaan.
Perdebatan ini semakin memanas setelah netizen dan sejumlah media daring ramai membandingkan kronologi, tanda tangan, format ijazah, hingga skripsi yang dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip akademik, termasuk standar administrasi UGM pada era 1980-an. Polemik tersebut berakar dari pemaparan awal Dr. Rismon Sianipar dan Roy Suryo, yang melalui pendekatan akademik membuka ruang diskursus hukum dan intelektual mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan presiden
Polemik ijazah ini tidak berhenti pada sosok Jokowi. Sorotan publik juga merambat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait dokumen kesetaraan pendidikan menengah (setara SLTA) yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan formal.
Pertanyaan pun mengemuka: apakah Gibran telah benar-benar memenuhi persyaratan administratif pendidikan untuk pencalonan, mengingat sebagian riwayat pendidikannya ditempuh di luar negeri? Pertanyaan ini menuntut klarifikasi resmi, bukan semata untuk menggugat individu, melainkan demi menjaga integritas hukum dan etika dalam proses pencalonan pejabat publik.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka: apakah negara telah menerapkan standar yang sama bagi seluruh warga negara, ataukah terdapat perlakuan khusus bagi keluarga penguasa? Belakangan, Roy Suryo bahkan menduga adanya aturan dalam regulasi KPU yang memuat pasal pengecualian tertentu terkait kesetaraan pendidikan setingkat SLTA tersebut.
Dari perspektif hukum dan demokrasi, perjuangan para tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dr. Tifa, dan Beathor tidak semata-mata tentang ijazah. Mereka mewakili hak rakyat untuk memperoleh transparansi dan kejujuran dari pemimpin tertinggi negara.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat ketidakabsahan atau rekayasa dokumen, maka perjuangan mereka akan tercatat sebagai pembelaan atas hak publik dan supremasi hukum. Sebaliknya, jika semua dokumen terbukti sah, maka polemik ini tetap menjadi pelajaran penting tentang perlunya keterbukaan informasi dan kesiapan pejabat negara untuk diuji, bukan dilindungi oleh kekuasaan.
Dalam negara demokrasi, kritik tajam terhadap penguasa bukanlah bentuk permusuhan, melainkan mekanisme kontrol sosial. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam konteks polemik terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, saya telah menulis banyak artikel untuk mengurai persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Beberapa judul artikel tersebut antara lain: “Mengapa Jokowi Tak Pernah Menjawab Langsung Polemik Ijazahnya? Sebuah Respons yang Bisa Mencerminkan Kualitas Demokrasi Kita,” “Polemik dan Pro Kontra Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Siapa yang Salah?” “Cara Obama Membuktikan Lahir di Hawaii Patut Dicontoh oleh Presiden ke-7 RI,” serta “Pasca Membicarakan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Nama Beathor Bersinar Terang Bak Meteor.”
Dari keseluruhan tulisan tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa kisruh ini sejatinya tidak perlu terjadi apabila sejak awal mantan Presiden Jokowi bersedia membuka dokumen pendidikannya secara transparan kepada publik. Sebagai perbandingan, ketika Barack Obama pernah dituduh bukan warga asli Amerika Serikat, ia segera meredakan polemik tersebut dengan menunjukkan akta kelahiran aslinya, sehingga isu tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan.
Saya juga meyakini bahwa seorang warga negara tidak boleh dipidana hanya karena mempertanyakan keaslian ijazah pemimpin atau mantan pemimpinnya. Menindak kritik melalui jalur kriminal bukan hanya berpotensi memperkuat kecurigaan publik, tetapi juga melukai prinsip keadilan dan kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Selama pertanyaan yang diajukan bersifat faktual dan dilandasi niat mencari kebenaran—bukan fitnah atau caci maki pribadi—maka perjuangan para pengkritik justru harus ditempatkan sebagai bagian penting dari kontrol publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai penutup, perlu saya tegaskan makna dari istilah pejuang rakyat sejati. Yang dimaksud dengan pejuang rakyat sejati adalah sosok yang berjuang dengan tulus dan ikhlas demi kepentingan rakyat banyak, bukan demi keuntungan pribadi, golongan, atau ambisi kekuasaan. Mereka berani menghadapi risiko, berdiri tegak melawan tekanan, dan menempuh jalan terjal demi menegakkan kebenaran. Setiap tindakan mereka berpijak pada kejujuran, integritas, dan nurani moral.
Istilah ini bukan sekadar gelar, melainkan cerminan komitmen dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat, sekalipun perjuangan itu menuntut pengorbanan besar. Sikap seperti ini adalah wujud keberanian moral yang selayaknya mendapat apresiasi tinggi dari seluruh rakyat Indonesia.
Khusus bagi Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, dr. Tifa, dan Beathor Suryadi, mereka telah menunjukkan sikap yang tidak lazim dalam iklim politik yang penuh tekanan: pantang mundur melawan arus. Mereka berani mempertanyakan keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi serta mengkritisi status kesetaraan pendidikan SLTA Wakil Presiden Gibran—sebuah langkah yang ibarat berhadapan dengan tembok besar yang sangat kuat dan kokoh. Namun demikian, mereka tetap berdiri tegak, tidak gentar, dan terus melangkah demi menegakkan kebenaran.
Apabila kelak pengadilan atau lembaga independen benar-benar menyatakan adanya pelanggaran serius dalam dokumen pendidikan seorang pejabat negara, maka tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, dr. Tifa, dan Beathor Suryadi patut dikenang sebagai pejuang rakyat sejati. Mereka bukan hanya pengkritik, tetapi penjaga moralitas republik—yang menolak tunduk pada intimidasi demi menegakkan kejujuran dalam sejarah bangsa. Tentu masih banyak nama lain yang turut berjuang, namun empat sosok tersebut telah merepresentasikan kegelisahan dan suara publik dalam kapasitas yang sangat berarti.