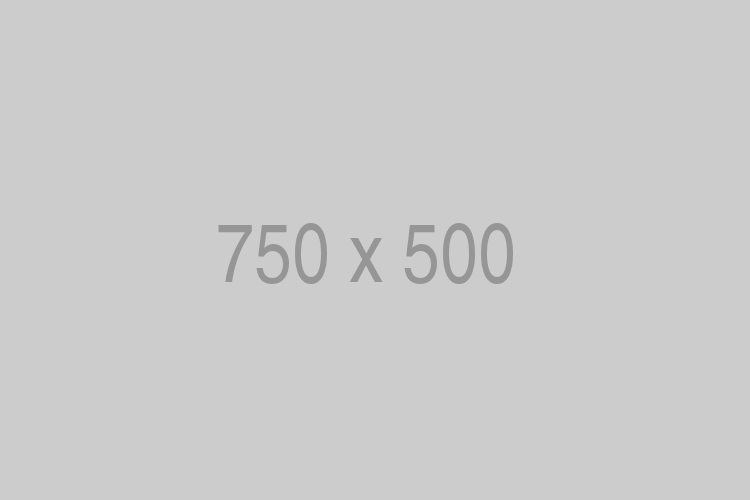Hidup Damai pun Berat, Apalagi Konfrontasi: Blok Ambalat atau Sabah — Mandek, Sengketa, atau Kelola Bersama? Tapi Rakyat Juga Siap Berperang

RAKYAT Indonesia ingin melihat bahwa negara hadir, bukan hanya di ruang negosiasi, tapi juga di garis terdepan kedaulatan nasional
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Hidup damai di era global yang penuh ketidakpastian sudah menjadi tantangan berat. Tekanan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik di kawasan, perubahan iklim, dan fluktuasi sosial menjadikan stabilitas nasional sebagai komoditas yang sangat mahal. Dalam suasana seperti ini, memilih konfrontasi bukan hanya menantang logika, tapi juga mengguncang tanggung jawab moral terhadap nyawa rakyat dan masa depan bangsa. Namun, ketika kedaulatan dipertaruhkan, tak ada ruang bagi ketakutan.
Blok Ambalat, sebuah wilayah strategis di Laut Sulawesi yang kaya akan sumber daya minyak dan gas, telah lama menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Kawasan yang masuk dalam area ND6 dan ND7 versi peta Malaysia ini mencakup area sekitar 15.235 km² dan menyimpan cadangan energi yang diperkirakan bernilai triliunan dolar. Sengketa ini bermula dari klaim unilateral Malaysia dalam peta tahun 1979, yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayah Sabah tanpa dasar hukum internasional yang kuat. Klaim itu segera ditolak Indonesia dan beberapa negara lain karena bertentangan dengan prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Berdasarkan UNCLOS, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985, Ambalat masuk ke dalam landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia karena berada dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Ini juga didukung oleh Perjanjian Landas Kontinen Indonesia–Malaysia 1969, yang tidak menyebut Ambalat sebagai bagian dari wilayah Malaysia. Namun, alih-alih membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional, Indonesia memilih jalur diplomasi bilateral.
Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Indonesia belajar dari pengalaman pahit dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan Malaysia pada 2002. Mahkamah Internasional mengakui kedaulatan Malaysia karena dinilai lebih aktif mengelola dan mengadministrasi kedua pulau tersebut. Sejak saat itu, Indonesia memperkuat pendekatan diplomatik dan tindakan konkret di lapangan, seperti pembangunan mercusuar di Karang Unarang dan peningkatan patroli TNI AL di kawasan Ambalat.
Pemerintah Indonesia tetap berpegang pada prinsip non-konfrontatif. Bahkan ketika terjadi insiden bersenggolan antara KRI Tedong Naga dengan kapal perang Malaysia KD Rencong pada 2005, pendekatan diplomasi tetap dikedepankan. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai pemerintahan Indonesia menahan diri untuk tidak membawa konflik ini ke eskalasi militer, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Namun, tuduhan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap lemah atau takut terhadap Malaysia dalam isu Ambalat adalah pandangan yang emosional dan tidak berdasar. Prabowo adalah mantan jenderal tempur, eks Danjen Kopassus, dengan pengalaman luas dalam operasi militer. Keputusan untuk menahan diri bukan cerminan kelemahan, melainkan strategi pertahanan menyeluruh yang memahami dinamika hukum, politik, dan ekonomi global. Prabowo memahami bahwa kekuatan militer adalah alat terakhir—bukan alat utama—dalam hubungan internasional, sesuai dengan prinsip Piagam PBB Pasal 51.
Pada Juni 2025, Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim menggelar pertemuan bilateral di Kuala Lumpur. Hasilnya adalah kesepakatan untuk menjajaki kerja sama pengelolaan bersama (joint development) di kawasan Ambalat, sembari terus menyelesaikan batas wilayah melalui jalur diplomasi. Ini adalah langkah realistis yang tidak mengorbankan kedaulatan, tapi membuka ruang kemanfaatan ekonomi di tengah ketidakpastian regional dan tekanan global.
Joint development bukan kompromi, melainkan mekanisme kerja sama yang telah digunakan dalam banyak sengketa maritim dunia. Bahkan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, atau Vietnam dan Tiongkok, pernah menggunakan skema serupa untuk menghindari konflik terbuka sembari tetap mengedepankan klaim masing-masing secara diplomatis. Dalam konteks Ambalat, skema ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk tetap memperkuat kehadiran hukum dan fisik di wilayah tersebut, sekaligus menghindari konfrontasi yang tidak produktif.
Namun kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam zona nyaman diplomasi. Peningkatan kekuatan pertahanan maritim, pembangunan infrastruktur perbatasan seperti mercusuar dan radar laut, serta patroli militer aktif harus menjadi agenda berkelanjutan. Rakyat Indonesia ingin melihat bahwa negara hadir, bukan hanya di ruang negosiasi, tapi juga di garis terdepan kedaulatan nasional.
Kondisi politik di Malaysia sendiri terus berubah. Tekanan dari oposisi seperti Partai Perikatan Nasional yang kembali mengangkat isu Sabah dan ND6–ND7 untuk kepentingan politik domestik berpotensi memperkeruh suasana. Namun respons yang tenang dan terukur dari kedua pemerintah menunjukkan kedewasaan diplomasi ASEAN, di mana stabilitas kawasan lebih penting dibandingkan provokasi jangka pendek.
Di tengah semua itu, satu hal tetap pasti: rakyat Indonesia tidak takut berperang. Sejak zaman penjajahan, dari Aceh hingga Papua, dari Timor Timur hingga Natuna, semangat mempertahankan kedaulatan menjadi bagian dari DNA bangsa ini. Namun rakyat juga tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada keberanian menyulut konflik, melainkan pada kecerdasan memilih waktu, tempat, dan alasan untuk berperang—jika memang tidak bisa dihindari.
Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa ia tidak tunduk pada tekanan populisme yang menuntut aksi militer cepat. Sebaliknya, ia mengedepankan rasionalitas, strategi, dan tanggung jawab sebagai kepala negara. Dan rakyat pun mendukung, karena hidup damai saja sudah berat—apalagi jika harus berkonflik.
Namun jika harga diri bangsa dilecehkan dan kedaulatan diganggu, Indonesia tak akan ragu. Diplomasi adalah pilihan utama, tetapi pertahanan adalah garis terakhir yang tidak akan pernah ditinggalkan. Karena bagi Indonesia, hidup damai adalah hak, dan mempertahankan tanah air adalah kewajiban suci yang tak bisa ditawar.