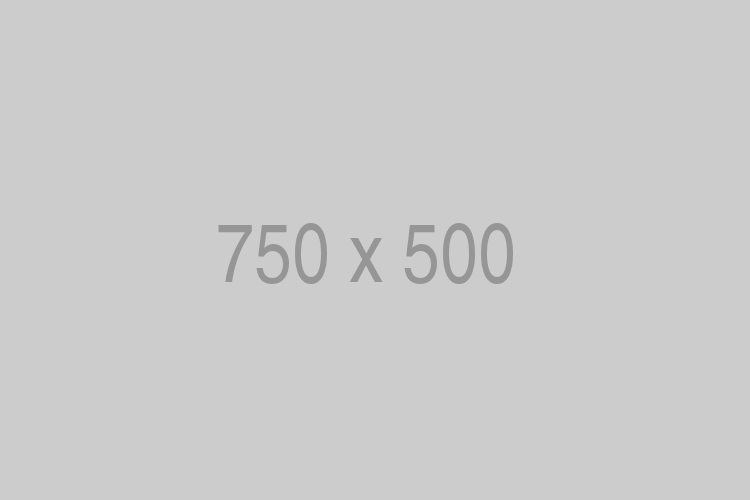Gubernur Bukan Panglima : Menakar Kewenangan Dedi Mulyadi terhadap Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat

FUNGSI pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan komando layaknya seorang panglima
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Bapak Aing atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), menjadi sorotan publik sejak hari pertama masa jabatannya. Berbagai kebijakan yang ia canangkan menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian menilai langkah-langkah KDM sebagai progresif, tegas, dan pantas mendapat banyak pujian publik.
Namun, tidak sedikit pula yang menganggap kebijakan-kebijakannya kontroversial. Tak hanya itu, bahkan mungkin publik menilai kebijakan KDM itu berpotensi melampaui batas-batas kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah yang bersifat otonom.
Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan mencakup penghapusan wisuda di jenjang TK hingga SMA, larangan study tour ke luar provinsi, serta pengiriman siswa bermasalah untuk menjalani pembinaan di barak militer. Selain itu, kebijakan kontroversial lainnya termasuk wacana menjadikan prosedur vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial, serta penerapan jam malam bagi pelajar di Provinsi Jawa Barat.
Seluruh kebijakan tersebut perlu dijadikan sebagai titik masuk penting untuk mengkaji posisi dan kewenangan seorang gubernur.
Dalam konteks ini, kajian tersebut tentu harus dikaitkan dengan kebijakan bupati dan wali kota dalam kerangka hukum tata negara serta prinsip otonomi daerah. Hal ini wajar, mengingat wali kota dan bupati juga merupakan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti gubernur, walikota dan bupati juga diusulkan oleh partai politik yang berbeda-beda sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Salah satu kebijakan awal KDM yang menimbulkan perdebatan adalah larangan study tour sekolah ke luar provinsi. Kebijakan ini diberlakukan secara tegas, termasuk melalui pemecatan atau penonaktifan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang dianggap melanggar surat edaran sebelumnya.
Meskipun larangan tersebut dapat dipahami dari sisi sosial, penegakan sanksinya menimbulkan pertanyaan penting. Salah satunya adalah terkait relevansi kewenangan gubernur dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap aparatur sekolah yang berada di bawah struktur Dinas Pendidikan Kota Depok.
Dalam hal ini, jika Pemerintah Kota Depok memutuskan untuk memperbolehkan penyelenggaraan study tour, maka potensi konflik kewenangan dapat muncul. Artinya, prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur urusan pendidikan di wilayahnya masing-masing.
Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah program pembinaan siswa bermasalah melalui pelatihan di barak militer. KDM menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari pendidikan karakter, yang dilaksanakan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Namun, program ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai berisiko melanggar hak asasi anak karena mungkin diterapkan tanpa dasar hukum yang kuat.
Lebih jauh, pelaksanaannya dikhawatirkan melampaui batas kewenangan seorang gubernur, yang dalam sistem pemerintahan daerah pada dasarnya memiliki peran yang lebih bersifat koordinatif.
Kontroversi serupa juga muncul terhadap kebijakan pelarangan wisuda dari jenjang TK hingga SMA, serta usulan menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Kedua kebijakan ini meski dibungkus dengan dalih efisiensi anggaran dan pengendalian kelahiran, banyak dinilai mengabaikan pendekatan yang inklusif. Selain itu kebijakan ini juga mungkin dinilai tidak melalui mekanisme partisipatif publik maupun pertimbangan yuridis yang memadai. Semua hal ini boleh jadi menunjukkan pola kebijakan “top-down” yang tidak sesuai dengan asas desentralisasi.
Lebih jauh, pada 16 Mei 2025, KDM juga menyampaikan kebijakan baru berupa penerapan jam malam bagi pelajar yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2025. Langkah ini kembali mempertegas kecenderungan Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengambil keputusan kebijakan publik. Artinya, boleh jadi kebijakan KDM ini diambil tanpa melibatkan koordinasi yang memadai dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beragam respons dari masyarakat. Secara khusus, para kepala daerah di tingkat kabupaten/kota mungkin merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.
Dalam hal ini, munculnya aturan tersebut mungkin tidak dilandasi regulasi hukum formal seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui mekanisme legislatif. Kebijakan jam malam itu pada dasarnya hanya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK tertanggal 23 Mei 2025. Karena hanya berupa surat edaran, kebijakan ini mungkin saja tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa dan tidak dapat diberlakukan secara mengikat.
Dalam konteks hukum tata negara, posisi gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 91 dan 92, dijelaskan bahwa gubernur bertugas sebagai koordinator yakni, pembina dan pengawasan pemerintahan daerah kabupaten/kota, bukan atasan langsung bupati atau wali kota.
Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh gubernur tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan komando layaknya seorang panglima. Artinya, peran gubernur seharusnya dipahami sebagai mekanisme untuk memperkuat kapasitas serta menjaga harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan.
Lebih tegas lagi, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Ini berarti bahwa bupati dan wali kota memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya masing-masing, tanpa harus tunduk pada instruksi gubernur yang tidak memiliki dasar hukum mengikat.
Dalam praktik pemerintahan yang demokratis, keberagaman konteks lokal di setiap kabupaten/kota menuntut diterapkannya pendekatan kebijakan yang adaptif dan partisipatif. Ketika gubernur mengeluarkan suatu kebijakan umum, seharusnya langkah tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan kepala daerah setempat.
Setiap formulasi kebijakan dalam bentuk regulasi yang memiliki legitimasi hukum, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), perlu disusun bersama DPRD provinsi sebelum diterapkan. Dalam hal ini partisi publik adalah hal krusial. Disamping itu, peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan regulasi nasional lainnya harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan aturan turunannya, agar selaras secara hierarkis dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.
Kegagalan dalam melakukan proses ini berpotensi menciptakan disharmoni dan bahkan konflik kewenangan.
Fenomena ini memperlihatkan pentingnya penguatan pemahaman atas relasi kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah. Gubernur tidak memiliki hak untuk memaksa kepala daerah kabupaten/kota melaksanakan kebijakan yang tidak sesuai dengan karakteristik daerahnya atau tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Sebaliknya, kepala daerah di tingkat bawah justru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri dan akuntabel dalam koridor konstitusi dan undang-undang.
Dalam semangat demokrasi lokal, gubernur seyogianya berperan sebagai mitra koordinatif, bukan komandan atau panglima. Kolaborasi yang sehat antara gubernur dan bupati/wali kota harus dibangun atas dasar penghormatan terhadap prinsip otonomi daerah, supremasi hukum, serta keberpihakan pada kepentingan publik. Ketika prinsip-prinsip tersebut dijadikan landasan, maka pembangunan daerah tidak hanya akan berjalan efektif, tetapi juga mencerminkan keadaban demokrasi dan penghargaan terhadap keragaman sosial yang ada di masyarakat.
Dengan demikian, penataan hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat ke depan perlu ditopang oleh kejelasan batas kewenangan. Hal penting lainnya adalah keterlibatan publik serta mekanisme akuntabilitas yang transparan, yang keduanya sangat mendesak untuk diperkuat.
Gubernur, dalam posisinya sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, semestinya mendorong sinergi, bukan dominasi; mengayomi, bukan memerintah secara sepihak. Tugas pembinaan dan pengawasan terhadap wali kota dan bupati harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari fungsi gubernur dalam membantu Presiden Republik Indonesia.