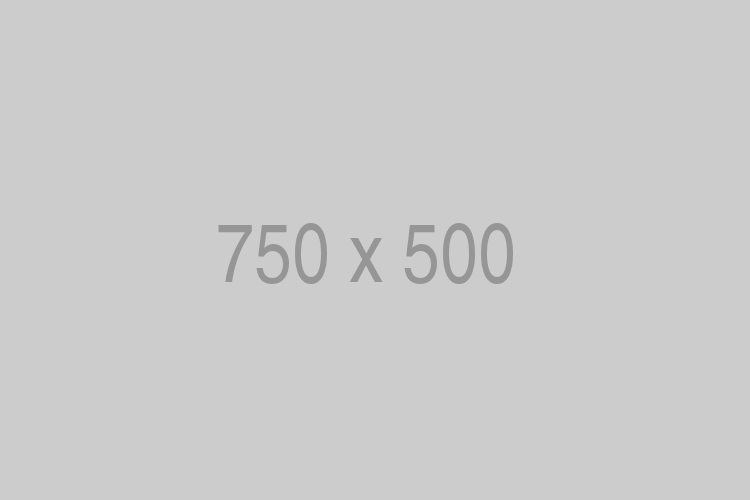Penuntasan Masalah RSSW dan Monorel ala Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Tepat!

GAGASAN Pramono yang berinisiatif menyelesaikan masalah-masalah lama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga patut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat.
Oleh : Sugiyanto (SGY)
Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT)
Sebelum melanjutkan artikel ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dalam menangani persoalan RSSW dan tiang monorel. Solusi yang beliau ajukan sangat tepat, namun tetap perlu berlandaskan pada tiga rekomendasi BPK serta melibatkan BUMN PT Adhi Karya dan PT Jakarta Monorail.
Selain itu, gagasan Pramono yang berinisiatif menyelesaikan masalah-masalah lama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga patut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Sebuah terobosan kebijakan yang jarang dipikirkan oleh banyak kepala daerah lainnya.
Dalam konteks tersebut, Pramono telah melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas dua isu penting yang telah lama terbengkalai. Kedua persoalan serius tersebut meliputi lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) serta keberadaan tiang-tiang monorel yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Terkait lahan RSSW, Gubernur Pramono berencana membangun rumah sakit tipe A di atas lahan yang sebelumnya dimiliki oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pramono meminta pendampingan dari KPK agar proses pemanfaatan lahan berjalan sesuai koridor hukum serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Menurut informasi dari KPK, penyelidikan terhadap kasus RSSW telah dihentikan sejak tahun 2023 karena tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum. Namun demikian, pendampingan KPK dalam pembangunan rumah sakit tersebut tetap diperlukan sebagai bentuk pencegahan risiko hukum.
Adapun mengenai tiang-tiang monorel, Gubernur Pramono juga mengusulkan rencana pembersihan dan pembongkaran tiang yang tersebar di sepanjang Jalan Rasuna Said dan kawasan Asia Afrika. Ia menegaskan bahwa jika persoalan hukum terkait keberadaan tiang-tiang tersebut telah tuntas, maka pembongkaran akan segera dilakukan.
Keberadaan tiang-tiang monorel tersebut kerap menimbulkan kecelakaan, mengganggu estetika kota, dan memicu kemacetan lalu lintas. Atas dasar itu, rencana Gubernur Pramono untuk membongkar tiang-tiang monorel tersebut dapat dinilai sebagai langkah yang tepat.
Saya memahami dan mengikuti kedua persoalan tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, saya mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Gubernur Pramono Anung Wibowo. Namun, dalam memberikan dukungan, perlu diingat bahwa setiap kebijakan beliau tetap harus diiringi dengan masukan serta informasi yang akurat dari berbagai pihak. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif yang dapat merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat.
Dalam konteks kasus RSSW, perlu diketahui bahwa persoalan ini bermula dari pembelian lahan oleh Pemprov DKI pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggaran sebesar Rp 755 miliar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan DKI Jakarta tahun 2014, ditemukan adanya indikasi kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar.
BPK mengeluarkan tiga rekomendasi utama: membatalkan pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi dengan YKSW; memulihkan indikasi kerugian daerah; serta meminta pertanggungjawaban YKSW untuk menyerahkan lokasi fisik tanah yang sesuai dengan penawaran awal, yaitu di Jalan Kyai Tapa, bukan di Jalan Tomang Utara. BPK Pusat kemudian memperkuat temuan tersebut melalui audit investigatif dan menegaskan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 173 miliar.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa siapa pun yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dipidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp 500 juta. Oleh karena itu, langkah Gubernur Pramono untuk melibatkan KPK sudah tepat, namun rekomendasi BPK tidak bisa diabaikan karena merupakan bagian dari hukum positif.
Bahkan secara kelembagaan, BPK memiliki kedudukan lebih tinggi karena dibentuk berdasarkan konstitusi, sedangkan KPK melalui undang-undang. Dalam hal ini, selain meminta pendampingan KPK, Gubernur juga sebaiknya meminta pertimbangan dan pendapat resmi dari BPK, baik perwakilan DKI Jakarta maupun BPK Pusat, agar rencana pembangunan RS tipe A di lahan RSSW tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Terkait persoalan tiang-tiang monorel, saya menegaskan bahwa tidak ada masalah hukum dalam pembangunan fisiknya karena proyek ini dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN. Pembangunan dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan model unsolicited proposal atau inisiatif swasta. Karena itu, keberadaan tiang-tiang monorel tidak bisa serta-merta dibongkar tanpa menyelesaikan terlebih dahulu persoalan kontraktual yang terkait.
Proyek monorel ini dimulai pada tahun 2004 pada masa Gubernur Sutiyoso dan diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun proyek terhenti karena berbagai kendala, termasuk masalah finansial, hukum, dan sengketa lahan.
Upaya melanjutkan proyek kembali dilakukan oleh Gubernur Joko Widodo pada tahun 2013 melalui kerja sama dengan PT Adhi Karya dan PT Jakarta Monorail (PT JM), namun kembali terhenti akibat konflik kepemilikan dan pendanaan antara kedua pihak tersebut. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama secara resmi membatalkan proyek ini pada tahun 2015.
Pemerintah sempat merencanakan untuk melanjutkan proyek ini dengan estimasi biaya sebesar USD 496,5 juta atau sekitar Rp 4,42 triliun, namun gagal karena belum adanya kesepakatan nilai ganti rugi. Audit BPKP menyetujui nilai kompensasi sebesar Rp 204 miliar, jauh di bawah klaim PT JM yang mencapai Rp 600 miliar.
Konflik ini juga dipengaruhi oleh belum tuntasnya perbedaan antara PT Adhi Karya dan PT Jakarta Monorail (PT JM) terkait pembiayaan pembangunan tiang monorel. Pada akhirnya, pada tahun 2013, PT Adhi Karya keluar dari konsorsium. Dengan demikian, tiang-tiang monorel yang telah dibangun menggunakan biaya PT Adhi Karya menjadi aset milik PT Adhi Karya. Sementara itu, PT JM tetap memegang hak konsesi atas pembangunan jalur monorel, yakni jalur hijau dan jalur biru.
Pada tahun yang sama, PT JM kemudian bekerja sama dengan PT Ortus Infrastructure Capital Limited, selaku pemegang saham mayoritas setelah keluarnya PT Adhi Karya dari konsorsium. Namun, akibat kebuntuan tersebut, proyek tidak dapat dilanjutkan, dan tiang-tiang monorel yang telah berdiri sejak 2015 pun dibiarkan terbengkalai hingga kini.
Karena proyek ini merupakan inisiatif swasta, setiap langkah penyelesaian harus mengacu pada klausul dalam kontrak kerja sama, yang menetapkan bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase internasional di Prancis. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tiang-tiang monorel tidak bisa dilakukan secara sepihak. Seluruh pihak harus dilibatkan secara formal, termasuk BPK, BPKP, PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Jakarta Monorail.
Saya mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membuka rencana penataan atau pembongkaran tiang-tiang monorel secara terbuka dan transparan. Alternatif berupa pemberian kompensasi dalam bentuk proyek lain yang saling menguntungkan dapat menjadi solusi efektif. Tidak menutup kemungkinan, PT Adhi Karya dan PT Jakarta Monorail bersedia menyetujui pembongkaran tanpa menuntut ganti rugi, selama prosesnya ditempuh melalui pendekatan hukum yang tepat dan komunikasi yang baik.
Sebagai penutup, yang terpenting dari keseluruhan proses ini adalah memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai persoalan internal antarperusahaan menyebabkan terbengkalainya proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi publik. Pemprov DKI Jakarta harus bertindak hati-hati, cermat, dan tetap mengedepankan prinsip hukum dan keadilan dalam menangani kedua persoalan ini.