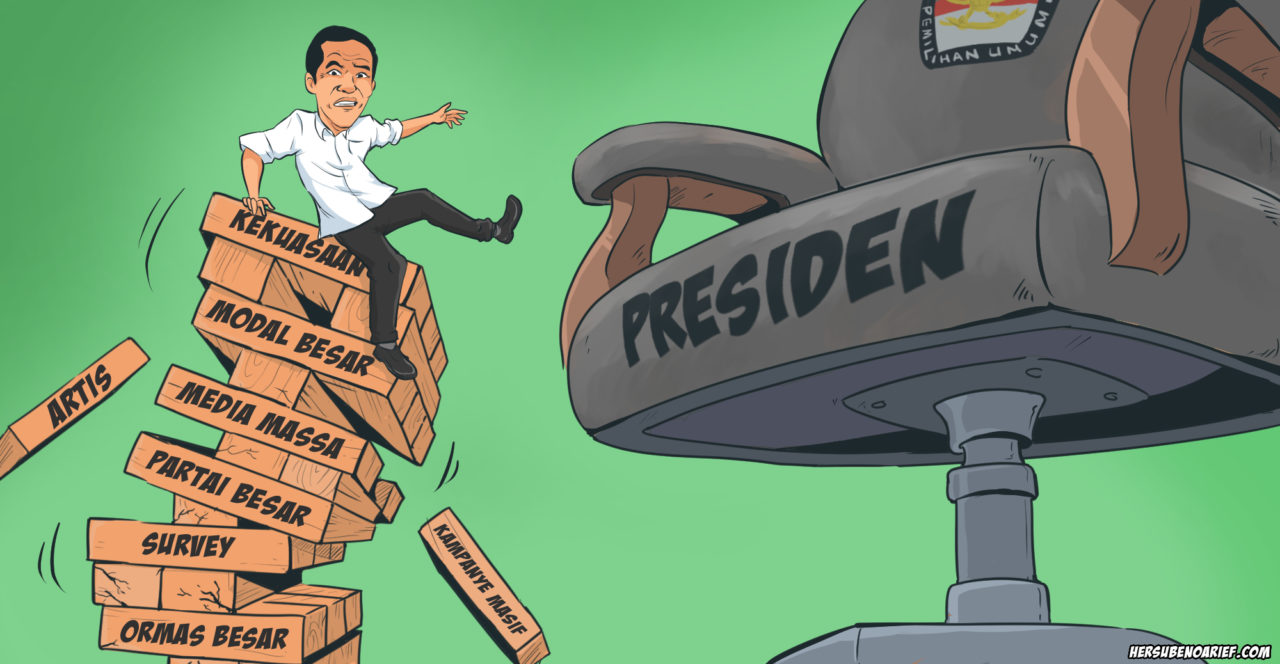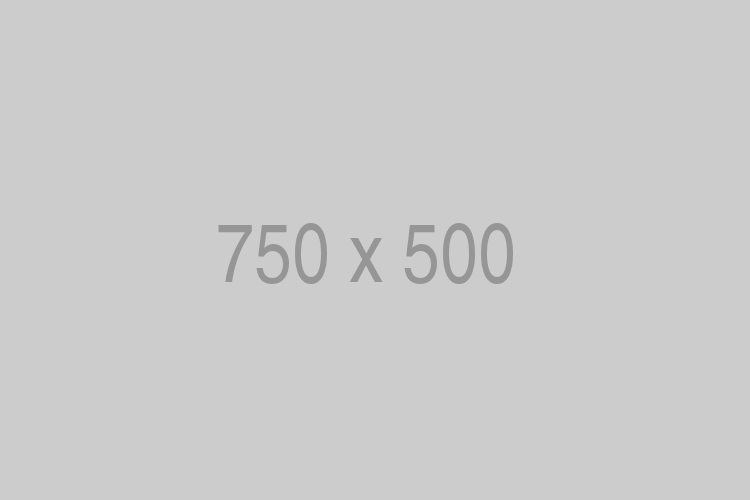Mewaspadai "Limbah" Perang Dagang China dan Perjuangan Kembali Kepada Konsensus Dasar

"...UNTUK MENUNJUKKAN kepada penjajah bahwa tanah kami tidak akan pernah menjadi tanah mereka. Tanah air kami adalah milik kami sendiri. Dan selama orang kulit putih masih hidup, mereka tidak akan pernah bisa menaklukkan tanah kami. Dan mereka juga tidak akan pernah menggantikan kami...”, demikian pesan pelaku penembakan massal di dua masjid di Selandia Baru.
Guncangan sosial, politik dan keamanan memang sedang menghantui banyak negara di barat. Sejumlah negara yang selama ini dikenal stabil secara politik dan tertib secara hukum mulai mengalami guncangan sosial dan keamanan. Setelah Perancis yang masih diguncang unjuk rasa rompi kuning (yellow vest) hingga saat ini.
Berikutnya adalah Selandia Baru sebagai contoh terdekat dari negara kita. Negara protektorat Kerajaan Inggris itu selama ini dikenal sangat stabil, tertib dan aman. Kita bahkan nyaris tidak mendengar berita buruk dari negara yang letaknya di pojok dunia itu.
Namun, pada tanggal 15 Maret 2019, ketenangan itu pecah, Selandia Baru terguncang. Kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa tragis, yaitu penembakan massal yang dilakukan secara sadis di dua Masjid, yaitu Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di kota Christchurch, Selandia Baru. Sebanyak 50 orang umat Islam yang sedang shalat diberondong dengan senjata standar militer tipe AR 15. Pelaku penembakan itu bahkan sambil melakukan live streaming saat aksi pembantian itu (bbc.com, 20 Maret 2019).
Brenton Harrison Tarrant adalah pelaku tunggal aksi penembakan massal itu. Tarrant berumur masih muda, 28 tahun. Persis Edward Snowden yang berumur muda, 29 tahun, ketika membobol dan membocorkan 1,7 juta dokumen rahasia milik National Security Agency (NSA). Katanya Tarrant berasal dari kelompok yang disebut “alt-right” (kanan alternatif).
Sebelum melakukan aksinya itu, Tarrant mengunggah pesannya di internet. Pesan itu dimuat di dalam sebuah dokumen setebal 73 halaman. Tarrant menyebut dokumennya itu sebagai Manifesto. Dokumen itu diberi judul “The Great Replacement” (Penggantian Hebat), dengan subjudul “Towards A New Society We March Ever Forward” (Menuju Masyarakat Baru Kita Bergerak Maju).
Penggantian hebat atau “great repleacment” adalah tentang ras kulit putih yang terancam punah dan digantikan oleh ras lain melalui “kolonisasi terbalik”. Tarrant menilai fakta statistik turunnya tingkat kesuburan, reproduksi dan populasi asli Eropa yang akan menyebabkan terjadinya penggantian etnis, ras dan budaya.
Menurut Tarrant, migrasi massal yang menyerbu negara-negara kulit putih adalah sebuah kolonisasi terbalik. Tarrant menganggap para imigran yang menyerbu “negara kulit putih” itu sebagai penjajah. “Negara kulit putih” yang dimaksudkan Tarrant dalam manifestonya itu diantaranya adalah Selandia Baru, Australia dan negara-negara Eropa.
Dalam dokumen itu, Tarrant diantaranya merujuk pada sebuah teori konspirasi bagi wajah baru ekstremisme kanan. Katanya ada sebuah rencana besar untuk memusnahkan "ras kulit putih" melalui migrasi massal dan kawin silang.
Bagi Tarrant, setiap orang harus hidup dalam dirinya sendiri. Memiliki budaya dan lingkungan organiknya sendiri, tidak terganggu oleh pengaruh orang luar. Oleh karena itu, Tarrant juga sangat menentang idealisme 'melting pot' yang dikembangkan Amerika Serikat.
Limbah Perang Dagang
Kita mengecam keras kekejaman dan kebiadaban yang dilakukan oleh Tarrant. Namun, motif dibalik lahirnya radikalisme “kulit putih” itu patut dicermati dan menjadi perhatian kita. Pandangan yang disampaikan oleh Tarrant itu sebetulnya juga menjadi masalah laten yang setiap saat bisa menjadi manifest di dalam kehidupan negara kita sendiri.
Sebagai contoh adalah polemik tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang juga menjadi masalah aktual yang diperdebatkan di dalam negara kita. Investasi dari China yang dicurigai membawa serta limbah berupa migrasi para kuli juga berpotensi mengguncang stabilitas di dalam negara kita.
Gelombang migrasi yang menyerbu negara-negara barat telah mengguncang stabilitas di sana. Serbuan migrasi dari Suriah dan Libya tersebut dapat kita katakan sebagai limbah beracun yang harus diterima oleh negara-negara Barat akibat ulah tangan mereka sendiri. Di masa depan, negara-negara Eropa bahkan diprediksi oleh banyak pemikir sosial dan politik akan mengalami devolusi peradaban.
Demikian juga revolusi digital yang sedang membentuk cara pandang dan sistem kosmopolitanisme yang mengabaikan konsep negara bangsa. Situasi kosmopolitanisme itu juga mendapat reaksi keras dari sejumlah kekuatan yang merasa terancam dan tertekan. Amerika Serikat, negara yang menjadi pelopor dari pasar bebas dan revolusi digital bahkan merasa terancam dan tertekan oleh senjatanya sendiri.
Globalisasi barang, jasa dan manusia melalui revolusi digital dan pasar bebas telah menjebol batas suku, batas ras, batas agama dan batas gender. Bahkan tembok konstitusi dan tanggul negara bangsa juga dijebol. Kini, sejumlah negara pengusung globalisasi, pasar bebas dan revolusi digital itu juga mulai menuai limbah beracunnya.
Diantara limbah beracun tersebut adalah kepungan produk palsu buatan China yang meruntuhkan industri nasional setiap negara. Demikian juga penghindaran pajak yang dilakukan dalam berbagai modus, seperti penyembunyian asset, hingga modus menciptakan banyak lisensi untuk sebuah produk agar terhindar pajak dari negara asal perusahaan itu, dll.
Amerika Serikat adalah negara yang sangat dirugikan oleh pemalsuan produk oleh China. Laporan yang dirilis Asosiasi Merek Internasional dan Kamar Dagang Internasional, misalnya menyebutkan nilai ekonomi global akibat pemalsuan dan pembajakan bisa mencapai 2,3 triliun US dolar pada tahun 2022. Nilai global barang-barang palsu tahun 2015 telah mencapai 1,7 triliun US dolar.
Amerika Serikat juga sangat dirugikan oleh praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berasal dari negaranya, seperti Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Starbucks, dll. Google misalnya mendirikan anak perusahaan di Irlandia, Amazon yang mendirikan perusahaan perantara di Luxembourg untuk pasar Eropa dan penjualan e-commerce, hingga Starbucks yang menyalurkan bahan baku lewat perusahaan perantara di Swiss, adalah salah satu contoh modus untuk menghindari pajak.
Karena itu, belajar dari kasus yang menimpa negara-negara di Eropa hingga teror berdarah di Selandia Baru digambarkan di atas, maka kita perlu mencermati dan mewaspadai limbah berancun akibat revolusi digital dan perang dagang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat kepada China.
Jika perang dagang itu berlangsung dalam tempo yang panjang, maka otomatis akan terjadi perlambatan ekonomi hingga resesi di negara tirai bambu itu. Dana Moneter Internasional (IMF) pada laporan tanggal 14 Desember 2018, misalnya memperkirakan PDB China tumbuh 6,2% di 2019, turun dari 6,4% yang diperkirakan sebelumnya.
Bisa dibayangkan jika ekonomi China mengalami perlambatan hingga mengalami resesi seperti yang sedang diskenariokan oleh Amerika Serikat. Maka situasi yang terjadi di Perancis dan negara Eropa dapat saja terjadi pada negara kita. Ketika penduduk Libya dan Suriah dipaksa bermigrasi ke Eropa untuk dapat survive.
Negara kita yang paling lemah border atau tanggulnya di kawasan Asia akan menjadi salah satu sasaran utama tempat pembuangan limbah beracun akibat dari resesi ekonomi di China tersebut. Limbah yang kami maksudkan adalah berupa serbuan migrasi pekerja dari China ke negara kita. Milyaran penduduk itu tentu berupaya survive ketika ekonomi di negaranya mengalami resesi.
Perhatikan juga data dari worldometers tentang jumlah penduduk China tahun 2019 yang telah mencapai 1,4 milyar atau tepatnya 1.418.708.765. Dengan rasio 18,41 persen dari penduduk dunia. Dengan penduduk sebanyak itu, bisa dibayangkan bagaimana jika negara itu mengalami resesi. Berapa ratus juta orang yang harus berjuang keluar dari negaranya untuk dapat survive atau bertahan hidup.
Karena itu, sebetulnya jika kita cermati, salah satu tujuan dari projek One Belt One Road (OBOR) adalah bukan untuk membantu pembangunan bangsa lain. Tujuan projek OBOR yang dilancarkan oleh China adalah untuk menopang negaranya sendiri agar bisa survive menciptakan lapangan pekerjaan untuk 1,4 milyar penduduknya.
Dengan menguasai rantai pasokan dunia melalui projek OBOR, maka ratusan juta lapangan pekerja akan terserap dalam sejumlah projek. Demikian juga penyerapan produk industri nasionalnya, seperti industri baja, dll otomatis akan terserap dalam projek infrastruktur tersebut. Tujuan lain dari projek OBOR adalah untuk menciptakan kanalisasi pembuangan limbah ekonomi dan politik yang berpotensi mengancam stabilitas di dalam negaranya.
Kembali Konsensus Dasar
Sejumlah negara besar saat ini sedang mencoba mengatasi limbah beracun dari globalisasi, pasar bebas, revoulusi digital dan gelombang migrasi yang telah merusak keseimbangan dan stabilitas di dalam negerinya.
Diantara upaya tersebut adalah perjuangan sejumlah negara untuk kembali kepada konsensus dasar yang membentuk negara mereka masing-masing. “Mereka sedang berjuang untuk pulang kembali kepada diri mereka”. Globalisasi dan revolusi digital memang telah menyeret setiap negara untuk keluar dari diri mereka dengan mengabaikan konsensus dasar yang membentuk dan menjaga eksistensi setiap negaranya.
Tidak ada yang dapat membantah bahwa lingkungan dan sejarah setiap negara pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap negara pasti mempunyai lingkungan dan sejarahnya sendiri. Lingkungan dan sejarah yang berbeda itu yang membentuk karakter dan melahirkan konsensus tertentu yang membentuk setiap negara.
Namun, konsensus dasar yang membentuk setiap negara itu sedang mengalami guncanga hebat, great disruption. Konsensus dasar atau dalam bahasa Arabnya disebut “kalimatun sawa” yang membentuk setiap negara itu kini kembali diuji oleh sejarah.
Rhenald Kasali melalui sejumlah bukunya memang telah membantu kita memperkenalkan fenomena disruption atau guncangan itu di dunia ekonomi. Sebetulnya yang patut dicermati dari situasi saat ini bukan semata masalah guncangan ekonomi. Disruption atau guncangan itu sedang merotohkan tatanan budaya, sosial dan politik yang membahayakan stabilitas setiap bangsa.
Karena itu, tidak salah jika jauh sebelum Rhenald Kasali membedah fenomena disruption di bidang ekonomi, pada tahun 1999, Francis Fukuyama telah menulis buku “The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order”.
Untuk mengatasi limbah beracun globalisasi, revolusi digital hingga gelombang migrasi, maka Inggris melakukan Brexit untuk kembali kepada konsensus dasar yang membentuk negara itu. Demikian juga Presiden Amerika Serikat Donnald Trump yang melancarkan gagasan pembangunan tembok di perbatasan Mexico juga untuk tujuan kembali kepada konsensus dasar Amerika dalam menghadapi guncangan dan terjangan gelombang globalisasi. Jauh sebelumnya, China juga telah merivisi ideologi pertentangan kelasnya untuk kembali kepada ke-China-annya.
Jika bangsa kita tidak mau menyadari untuk kembali kepada konsensus dasar, membangun kembali tanggul non fisik berupa penataan kembali sistem negara berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (sebelum amandemen), maka nasib bangsa kita akan menyusul negara seperti Perancis yang diterjang oleh kekuatan migran yang akan menguasai bangsa kita. end
Oleh: Haris Rusly Moti
Eksponen gerakan mahasiswa 1998 dan pemrakarsa Intelligence Finance Community (InFINITY)